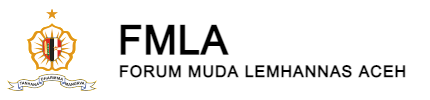Oleh Bung Syarif *
Memakai sarung bagi santri dayah adalah leksikon wajib, khususnya bagi laki-laki, akan tetapi dibeberapa dayah wanita di Aceh, tradisi pakai sarung sudah menjadi ruhnya santriwati, sebut saja Dayah Raudhatul Thulab, Aceh Besar. Lakon ini sering kami lihat saat mengantar dan menjemput keluarga.
Lantas, apa makna filosofis di balik kain sarung? tulisan ini mencoba mengurai secara apik, eksistensi kain sarung di pusaran nusantara, serta makna pilosofisnya. Berdasarkan beberapa catatan, kain sarung berasal dari Yaman. Awalnya sarung dipakai suku badui yang tinggal di Yaman. Saat itu, sarung berasal dari kain putih yang dicelupkan ke dalam neel yang merupakan pewarna bewarna hitam. Penggunaan sarung pun meluas. Tidak hanya ada di Semenanjung Arab saja, namun sarung juga sampai di Asia Selatan, Afrika, Asia Tenggara, Eropa, hingga Amerika.
Di Yaman, sarung dikenal dengan nama futah, izaar, wazaar atau ma’awis. Sedangkan, di Oman, sarung dikenal dengan nama wizaar. Kemudian orang Arab Saudi mengenalnya dengan nama izaar. Tekstil memang menjadi industri pelopor di era Islam. Pada era itu, standar tekstil masyarakat Muslim di Semenajung Arab sangat tinggi. Industri tekstil di era Islam memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Barat. Sat itu sarung telah menjadi pakaian tradisonal masyarakat Yaman.
Namun hingga sekarang, tradisi itu masih tetap melekat kuat. Sarung Yaman menjadi salah satu oleh-oleh khas tradisional dari Yaman. Kemudian orang-orang yang berkunjung ke Yaman biasanya menjadikan sarung sebagai buah tangan.
Sarung masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Saat itu sarung dibawa oleh para saudagar Gujarat dan Arab yang juga menyebarkan agama Islam. Sehingga dalam perkembangan berikutnya, sarung di Indonesia akhirnya identik dengan kebudayaan Islam.
Pada zaman penjajahan Belanda, sarung identik dengan perjuangan melawan budaya barat yang dibawa para penjajah. Kaum santri merupakan masyarakat yang paling konsisten menggunakan sarung, sedangkan kaum nasionalis abangan hampir meninggalkan sarung.
Sikap konsisten penggunaan sarung juga dijalankan oleh salah seorang pejuang yaitu KH Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh penting di Nahdhatul Ulama (NU). Suatu ketika, beliau pernah diundang Presiden Soekarno.
Protokol kepresidenan memintanya untuk berpakaian lengkap dengan jas dan dasi. Namun, saat menghadiri upacara kenegaraan, ia datang menggunakan jas tetapi bawahannya sarung. Padahal biasanya orang mengenakan jas dilengkapi dengan celana panjang.
Sebagai seorang pejuang yang sudah berkali-kali terjun langsung bertempur melawan penjajah Belanda dan Jepang, Abdul Wahab tetap konsisten menggunakan sarung sebagai simbol perlawanannya terhadap budaya Barat. Ia ingin menunjukkan harkat dan martabat bangsanya di hadapan para penjajah.
Sarung menjadi salah satu pakaian kehormatan untuk menunjukkan nilai kesopanan yang tinggi di masyarakat. Makanya, sarung sering dipakai untuk shalat di masjid. Biasanya laki-laki mengenakan atasan baju koko, sedangkan bawahannya menggunakan sarung. Sedangkan, wanita memakai atasan mukena, sedangkan bawahannya menggunakan sarung.
Perlu diperhatikan, di Indonesia sarung sendiri tidak hanya dikenakan oleh umat muslim. Tetapi, non-muslim juga mengenakan sarung. Seperti umat Hindu di Bali, bagi mereka sarung dikenakan untuk upacara-upacara adat dan keagamaan. Sementara, masyarakat di NTT, sarung dikenakan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk melindungi tubuh dari suhu malam hari yang agak dingin.

Dedi Mulyadi mantan Bupati Purwakarta menghubungkan sarung dengan kosmologi kesundaan atau cerita rakyat yakni Lutung Kasarung. Berdasarkan kisah tersebut menurutnya, Lutung Kasarung merupakan pewaris tahta kerajaan yang mengalami cobaan berupa pengasingan di hutan belantara, sebelum akhirnya diangkat menjadi pemimpin.
Dalam konteks ini, sarung berfungsi sebagai media kaderisasi kepemimpinan. Sebab saat seseorang memakainya, ada banyak peraturan yang tidak boleh ia langgar akibat penggunaan sarung tersebut. Dari sini lahirlah akhlak dan tercipta karakter yang kuat.
Dedi membagi “sarung” menjadi dua suku kata. Menurutnya, “sa” merupakan lambang keinginan manusia dengan segala unsur penciptaannya yang terdiri dari tanah, air, udara dan matahari. Unsur material inilah yang menurut dia harus dikurung. Hal ini tercermin dari suku kata yang kedua yakni “rung”.
Jika seluruh unsur material ini mampu dikurung, maka unsur hakikat kemanusiaan dalam diri manusia yakni ruh akan semakin menguat. Segala ketamakan manusia yang tercermin dari keempat unsur tersebut harus dikurung.
Ada juga yang mengartikan filosofi sebagai “sarune dikurung” (sarung). Artinya, sarung merupakan instruksi kehidupan, agar manusia mengedepankan rasa malu, tidak sombong, tidak arogan, apalagi sembrono. Saling menghormati diutamakan, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Tradisi memakai kain sarung menjadi cirikhas Alumni Santri Salafiyah, mudah sekali membedakan antara Pimpinan Dayah Alumi Dayah Terpadyu (Moderen) dengan Dayah Salafiyah (Tradisional), cukup melihat pada konsistensinya memakai kain sarung, walaupun ada satu dua pimpinan dayah yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lantas jika ada pejabat dinegeri ini yang memakai kain sarung, silahkan ditafsirkan sendiri ya? Hehe…
* Penulis adalah Kabid SDM dan Manajemen Disdik Dayah Banda Aceh, Direktur Aceh Research Institute (ARI), Sekretaris Forum Muda Lemhannas Aceh, Dosen FSH UIN Ar-Raniry, Mantan Aktivis`98, KAHMI Aceh